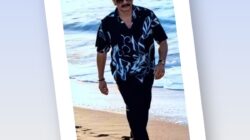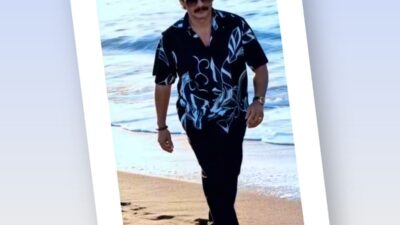“Saya bilang, bagaimana ceritanya ini? Mengapa kita ubah kesepakatan yang dibuat?” tanya Daeng Lawa sengit.
Suatu malam, cerita Daeng Lawa, dia mencari cara supaya berhenti dari warung coto yang belum lama dirintisnya itu. Dia menggeser tungku, agar nanti kualinya jatuh dan pecah. Dia memang sengaja mencari gara-gara agar bisa berhenti dan keluar dari situ. Itu skenarionya. Benar saja, begitu kualinya jatuh dan pecah, dia tidak mau lagi menjual coto.
Menurutnya, menjual coto menggunakan kuali dari tanah liat atau gumbang, ada ciri khasnya. Baunya lebih harum, dan kuah coto lebih tahan panasnya. Kalau jenis kayu bakarnya, boleh apa saja dipakai, yang penting dijaga apinya agar terus menyala. Selain itu, beda pula rasanya kalau menggunakan kayu bakar dibanding kompor. Pedagang, katanya, memilih menggunakan tungku kayu bakar karena lebih hemat atau irit dibanding bila kompor yang menggunakan minyak tanah atau gas.
Setelah kualinya pecah, mitra usahanya itu membujuknya agar tetap berjualan. Dia dianjurkan memasak kuah coto dengan menggunakan dandang aluminium. Namun, Daeng Lawa bersikeras bahwa beda rasanya kalau menggunakan periuk tanah liat. Aroma khas coto lebih terasa, dibanding bila dimasak dengan dandang aluminium. Kejadian ini kemudian mengakhiri perjalanannya di Kota Pahlawan tersebut. Daeng Lawa akhirnya pulang kembali ke Makassar.
“Semua penjual Coto Makassar itu lama prosesnya baru mereka bisa berhasil. Harus bersabar, dan bersabar terus,” katanya optimis.
Dia, katanya, sering medengar cerita para penjual coto, bahwa dahulu orangtuanya kalau menjual coto dengan cara dipikul. Mereka berkeliling sambil memikul jualannya. Bisa dibayangkan, betapa beratnya memikul gumbang beirisi kuah coto itu. Apalagi kalau dagangannya itu dipikul ke mana-mana. Cerita inilah yang terasa selalu menghibur dirinya, agar tak berhenti berusaha dan berdoa.
Bantu Nenek dan Beli Sepeda Motor
Daeng Lawa ingat, sewaktu bekerja jadi pelayan di Sidrap, dia diupah sebesar Rp2.500 sehari. Ini sudah termasuk honornya sebagai pembuat bumbu coto. Ketika posisinya naik sebagai pengiris daging, baik selama di Sengkang maupun Pari’risi, bayarannya meningkat menjadi Rp30.000 per hari.
Meski sejak pertama bekerja upahnya terbilang kecil, tapi dia sudah bertekad membantu neneknya di kampung. Upahnya yang masih Rp2.500 sebagai pencuci mangkuk, tidak dia habiskan. Dia rupanya ikut arisan per minggu, sebesar Rp2.500. Kalau arisannya naik, dia membantu keperluan neneknya.
“Saya belikan nenek saya, seng untuk memperbaiki rumahnya, membeli kursi, lemari, Al-Qur’an, dan banyak barang lainnya,” beber Daeng Lawa.