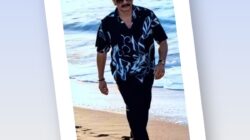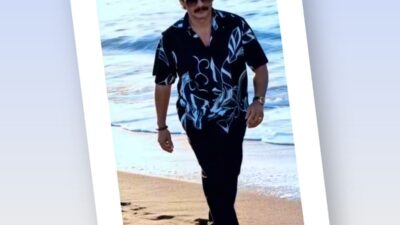Selama bininya dirawat di rumah sakit, istri Haji Sutte datang membezuk dengan naik ojek. Hutangnya sebesar Rp10 juta pada Haji Sutte, dia bayar dengan cara menggadaikan tanah orangtuanya.
Hidup Daeng Lawa tak melulu berhubungan dengan warung Coto Makassar. Dia sempat bekerja di pabrik penggilingan padi, yang tak jauh dari rumahnya. Karena pemiliknya bangkrut, dia pindah bekerja di bos lainnya, tapi masih punya hubungan saudara dengan bos sebelumnya. Di tempat penggilingan padi ini kerjanya rangkap sebagai penjaga gudang. Setelah itu, dia diajak sepupunya merantau keluar daerah, ke Masamba, ikut mobil kampas. Dia membawa barang campuran hingga ke Palu, Sulawesi Tengah.
Buka Coto Daeng Lawa di Surabaya
Tak terasa, kami sudah mengobrol lama di Coto Tangkia. Setelah membayar coto dan ketupat yang disantap, kami berjalan ke arah rumah Irmawati Daeng So’na, aktivis pertanian organik yang jadi teman seperjuangan Daeng Lawa. Rumahnya berada di seberang jalan. Lelaki berperawakan tinggi ini, bergabung dengan gerakan yang dibangun Daeng So’na lewat SePAKat, akronim dari Serikat Perempuan Pertanian Alami Kabupaten Takalar.
Setelah kami duduk di balai kayu yang berada di bawah rumah Daeng So’na, Daeng Lawa pun melanjutkan ceritanya.
Suatu ketika, dia melihat titik terang dalam hidupnya. Harapannya tumbuh, manakala seorang kenalannya di Sidrap mengajaknya berkongsi untuk membuka warung Coto Makassar sendiri. Kenalannya itu orang Sidrap, yang beristri wanita Jawa. Dia lantas mengajak Daeng Lawa ke Surabaya, Jawa Timur, untuk membuka warung Coto Makassar di sana. Daeng Lawa setuju. Mereka kemudian membuat kesepakatan bagi hasil dalam pengelolaan warung coto tersebut.
“Dia teman baik saya. Dia bukan pengusaha, mungkin orang kantoran tapi punya modal,” kisah Daeng Lawa.
Daeng Lawa kemudian berangkat ke Surabaya naik kapal laut. Temannya itu yang membayar ongkosnya. Selama di Kota Surabaya, dia tinggal di rumah kontrakan, dengan biaya sewa sebesar Rp11 juta/tahun. Lokasinya itu, seingat Daeng Lawa, seperti jalan kompas, bukan berada di jalan utama. Di situ pula mereka membuka warung coto, namanya warung Coto Daeng Lawa, menggunakan namanya. Harga semangkuk coto di warungnya dijual Rp25.000.
Untuk menjaga orisinalitas dan cita rasa cotonya, semua peralatannya dibawa dari Takalar, termasuk kuali tanah liat dibawa dari Paddinging. Kuali tanah liat itu dipesan dari Desa Pa’batangang, yang dikenal sebagai sentra pembuatan gerabah di Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar.
Awalnya, usaha warung coto mereka berjalan baik, Namun, belakangan temannya itu mengubah kesepakatan. Bukan lagi bagi hasil, sebagaimana pembicaraan di awal. Mitra bisnisnya itu malah menggajinya per hari, layaknya karyawan biasa. Tentu saja Daeng Lawa tak terima. Dia memprotesnya.