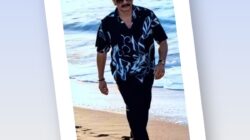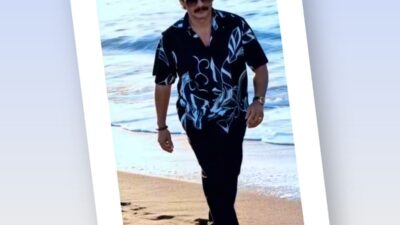Di satu sisi, aku sungguh benar-benar marah. Namun di saat itu pula aku sungguh tak berdaya dengan kondisiku yang jauh dari kampung halaman. Jadinya, aku hanya bisa memprotes dan merutuki diri sendiri. Kenapa peristiwa ini terjadi pada orang yang paling aku sayangi. Kenapa?.
“Lihat apa yang terjadi, kau lebih memilih kuliah dan jauh dari kampung halaman. Inikah yang kau maksud dengan pencapaian, gelar, kesuksesan? Bullsihit. Kau seharusnya menjaga Ibu dan adekmu. Bukankah kau paham kondisi rumah sepeninggalan ayah beberapa tahun lalu? Kau gagal jadi sosok kakak sekaligus anak, Haekal. Kau gagal!”
Kudengar kemarahan itu ditujukan padaku. Telunjuk dengan jari tegas mengarah ke wajahku. Aku menyalahkan diriku sendiri.
Pada kenyataannya memang demikian. Sehingga pantas bila aku ikut bertanggung jawab atas semua peristiwa yang terjadi pada adikku. Akibat peristiwa itu, aku terjaga sepanjang malam. Pikiranku kian kusut. Aku benar-benar putus asa.
Pukul jam 03.30, aku benar-benar capek. Capek fisik, lebih-lebih mental.
Sebelum beranjak tidur, aku berdoa dalam diam, penuh kepasrahan, atau lebih tepatnya putus asa.
“Tuhan, semoga ini menjadi malam terakhirku di dunia ini. Ambillah nyawaku sebagai balasan atas semua peristiwa yang terjadi. Semoga aku tak lagi melihat matahari di esok pagi. Aamiin.”
Barangkali doa ini terdengar naif. Namun malam itu, doa penuh kesusahan ini aku panjatkan. Aku lebih memilih kematian daripada harus menghadapi kenyataan hidup nan getir. Putus atas telah menyumbat akal sehatku.
Ternyata, aku kembali terbangun di pagi hari, pada pukul 09:24. Dalam hati aku berkata, “Sungguh ini suatu keajaiban.” Aku masih dapat menikmati matahari hari di pagi hari, meski tak demikian keinginanku.
Hari-hari selanjutnya, aku jalani dengan putus asa. Aku lebih banyak diam, bahkan enggan berkomunikasi dengan ibu dan kakak-kakakku.
Aku mencoba berkonsultasi mengenai masalahku ke salah seorang senior, sebut saja Ali. Kebetulan beliau sudah kuanggap seperti kakak sekaligus seorang psikolog.
Tanpa janji terlebih dahulu, aku mampir ke kostnya. Setiba di kostnya, dia kaget dengan kedatanganku yang tiba-tiba.
“Tumben datang, tak berkabar terlebih dahulu,” ujarnya.
“Hehe maaf, kebetulan lewat. Ada keperluan sama kakak. Jadi saya putuskan tuk mampir.”
“Emang ada perlu apa?”
Aku menceritakan semua musibah yang menimpaku. Aku sampaikan bahwa aku benar-benar kecewa pada diri sendiri, ibu dan kakak-kakakku.
Dia menjawab dengan melontarkan sebuah pertanyaan, “kamu tau gak apa yang paling buat orang tua bahagia?”