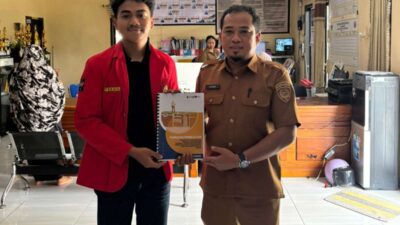Dr.Aksa, S.Pd.,M.Pd. yang sudah menulis sedikitnya 9 buku tersebut menyimpulkan dalam butir ketiga disertasinya, dalam konteks kolonialisme dan dinamika politik yang terus bertransformasi, ulama, dan sultan menempati posisi strategis yang berbeda, mencerminkan adaptasi terhadap perubahan konstelasi kekuatan. Intervensi VOC (Belanda) melalui instrumen hukum seperti Perjanjian “Ncake”, Perjanjian Bongaya, hingga “Lange Verklaring” (tanah yang tidak dimiliki secara sah akan menjadi milik negara) membentuk relasi kuasa yang asimestris dan menstimulasi resistensi kolektif ulama mengartikulasikan perlawanan melalui jihad. Sementara konflik di berbagai ranah mencerminkan ekspresi perjuangan rakyat berlandaskan pada nilai-nilai ideologis, keadilan sosial, dan prinsip-prinsip kemanusiaan universal.
Krisis legitimasi
Dr.Aksa, anak pasangan Mahmud-Siti Maryam ini, mengatakan, pada akhir abad XIX hingga awal abad XX, Kesultanan Bima menghadapi krisis legitimasi akibat sikap kompromistis Sultan Ibrahim (1881-1915) terhadap kolonial Belanda. Alih-alih menjadi pelindung (hawo ro ninu), ia dianggap tunduk pada hegemoni kolonial melalui serangkaian perjanjian, termasuk “lange verklaring” (1886) hingga kontrak 1908 yang meruntuhkan kedaulatan politik dan memperberat beban ekonomi rakyat dengan pajak kolonial.
“Kekecewaan kolektif melahirkan frustrasi sipil yang bermuatan spiritual, dipimpin ulama, bangsawan, dan pemimpin lokal serta termanifestasikan dalam Perang Ngali (1908-1909), Perang Kala (1909-1910), Perang Dena (1910), dan Rasa Nggaro. Perlawanan ini mencerminkan jihad sabil melawan ketidakadilan sekaligus menandai lahirnya kesadaran historis rakyat Bima untuk mempertahankan martabat, keadilan, dan identitas kolektif di tengah penetrasi colonial,” ujar Aksa.
Ia mengatakan, Perang Ngali merupakan perang sabil dan salah satu puncak resistensi masyarakat Bima terhadap kolonial Belanda. Perang ini berakar pada kekecewaan rakyat terhadap Sultan Ibrahim yang dianggap gagal menegakkan peran sebagai pelindung dan pengayom dan justru tunduk pada serangkaian perjanjian kolonial, termasuk kontrak politik (1908) yang memperberat pajak.
“Kondisi ini memicu perlawanan yang dipimpin ulama dan tokoh lokal dengan Salasa Ompu Kapa’a sebagai figur sentral,” kata Aksa mengutip Rosdiana (2022) dalam tulisannya yang dimuat dalam “Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra”, kemudian menambahkan, Perang Ngali tidak hanya bermakna politik, tetapi juga religius karena dipandang sebagai jihad sabil melawan ketidakadilan struktural dan dominasi kolonial.