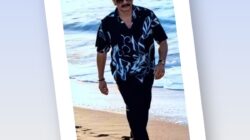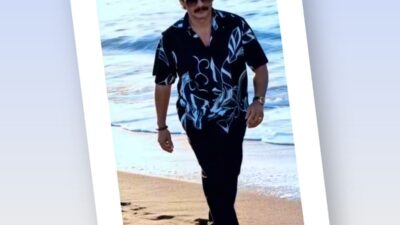– Festival Puisi Esai Jakarta ke-3, 2025. Total Lomba: Hadiah 185 Juta Rupiah
Oleh Denny JA
NusantaraInsight, Jakarta — Ada hari-hari ketika bumi tidak hanya retak oleh bencana,
tetapi juga oleh kesunyian kita.
Dan Sumatra, yang di akhir November- Desember 2025 menjadi ladang air mata, adalah salah satu hari itu.
Ketika 800 lebih nyawa hanyut dalam gelap,ketika bukit-bukit yang setia selama ribuan tahun runtuh seketika, ketika banyak keluarga hilang tanpa jejak, kita tahu.
Ini bukan lagi sekadar bencana alam. Ini adalah pesan, ditulis dengan air bah, tanah longsor,
dan jeritan yang tak terdengar oleh mikrofon mana pun.
Bumi tidak lagi menunggu kita sadar. Ia mengetuk dengan keras. Dengan banjir, ia mengetuk.
Dengan longsor, ia mengetuk.
Dengan desa dan kota yang tenggelam, dengan udara yang makin berat, dengan hutan yang lenyap seperti catatan harian yang dibakar, ia terus mengetuk, bertanya:
Masihkah kalian mencintaiku?
Atau kalian hanya mencintaiku ketika aku masih memberi,
namun melupakanku ketika aku terluka?
-000-
Pada bencana di Sumatra akhir 2025, air tidak turun begitu saja dari langit; ia mengalir di antara jejak keputusan manusia.
Di balik angka korban jiwa dan rumah yang hilang, ada sejarah pembalakan, alih fungsi lahan, kelapa sawit yang menggerus bukit, serta pengawasan yang lalai.
Banjir dan longsor itu bukan hanya “murka alam”, melainkan akumulasi dari kebijakan yang menempatkan keuntungan jangka pendek di atas keselamatan warga.
Karena itu, ketika puisi esai bicara tentang Sumatra yang menangis, ia tidak boleh berhenti pada ratapan. Esai dan Sastra yang bertanggung jawab harus berani menyebut aktor, struktur, dan pola kebijakan yang membuat desa-desa rapuh di hadapan hujan ekstrem.
Dari sana, empati tidak berhenti sebagai air mata di halaman buku, tetapi bergerak menjadi tuntutan atas tata ruang yang adil, perlindungan hutan, dan mekanisme tanggap bencana yang berpihak pada yang paling rentan.
Dalam kerangka itulah sebuah festival sastra layak menempatkan diri: bukan sekadar panggung nama, hadiah, dan promosi genre, melainkan ruang belajar bersama antara penyintas, aktivis lingkungan, peneliti, jurnalis, dan penulis.
Puisi esai, atau bentuk apa pun, hanya sah menyebut diri jembatan jika ia betul-betul menghubungkan pengalaman korban dengan pengetahuan kritis dan tindakan sosial nyata: diskusi kebijakan, penggalangan dukungan bagi komunitas terdampak, serta dokumentasi yang jujur atas luka yang terjadi.
-000-
Di sinilah puisi esai menemukan panggungnya. Bukan sekadar sebagai genre, melainkan sebagai jembatan spiritual antara tragedi dan kesadaran,
antara fakta dan empati,
antara data bencana dan air mata manusia.